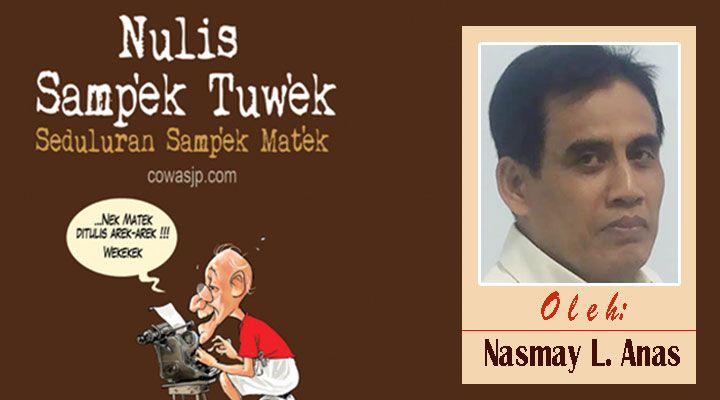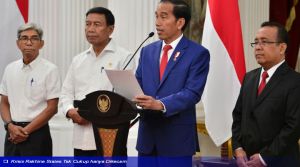COWASJP.COM – Yang menjadi syarat untuk menjadi kepala negara Islam adalah, "Agamanya, sifat dan tabiatnya, akhlak dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya. Jadi bukanlah bangsa dan keturunannya ataupun semata-mata inteleknya saja."
(Muhammad Natsir)
*
TANPA BERPRETENSI apa-apa, saya ingin mengatakan bahwa saya pernah bekerja tidak kurang dari 10 tahun bersama Dr. Mohammad Natsir. Saya bersama kawan-kawan, yang sebagian waktu itu masih berstatus mahasiswa, terlibat membantu beliau dalam pengelolaan keredaksian majalah Media Dakwah. Yaitu media yang diterbitkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Pusat, yang beliau pimpin. Terakhir, saya adalah Pemimpin Redaksi Media Dakwah, sebelum saya bergabung dengan Harian Jawa Pos biro Jakarta.
Tapi kami tidak hanya dilibatkan dalam bidang itu saja. Sebab, selain kegiatan redaksi, kami juga terlibat dalam sejumlah rutinitas beliau, yang karenanya juga jadi rutinitas kami. Sebut saja misalnya membuat brosur dan selebaran yang berisi tulisan-tulisan beliau, berkenaan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa saat itu.
Sebab, walaupun fisik beliau sudah uzur dimakan usia, namun semangat beliau untuk berjuang bagi kebaikan dan kemajuan bangsa ini tidak pernah kendor. Beliau benar-benar konsisten dengan sikap yang beliau patrikan dengan kata-kata: “Kalau dulu berdakwah melalui politik, sekarang berpolitik melalui jalur dakwah”.
Natsir tidak pernah lelah untuk menulis tentang setiap persoalan yang dihadapi bangsa. Beliau bahkan tidak pernah berhenti memberikan kritik yang membangun terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Orde Baru, baik politik, ekonomi maupun sosial budaya. Walaupun termasuk salah seorang tokoh yang sampai mati dicekal pemerintah ke luar negeri karena keterlibatan beliau menandatangani apa yang dikenal dengan “Petisi 50”, namun beliau tidak pernah berhenti memperjuangkan apa yang menurut beliau harus diperjuangkan.
Tidak jarang kami dipanggil ke rumah beliau di Jalan Jawa atau Jl. HOS Cokroaminoto no. 42 bahkan sampai larut malam, untuk mengoreksi kembali tulisan-tulisan beliau yang hendak diterbitkan jadi brosur. Dan mengapa brosur? Karena media-media yang ada jarang yang berani memuat tulisan-tulisan beliau yang tajam tanpa tedeng aling-aling. Apalagi topik-topik yang beliau bahas – seperti soal Azaz Tunggal Pancasila, Dwifungsi ABRI, sekularisasi dalam dunia pendidikan dan sejumlah topik serius lain – yang pastinya membuat para pemimpin redaksi media ketar-ketir.
Zaman itu adalah masa di mana media massa tidak sebebas seperti sekarang dan rejim Orba terkenal sangat sensitif dalam menyikapi pemberitaan oleh media massa. Jadi, kalau pun ada yang mau memuat, tapi editing-editing yang dilakukan redaksi membuat beliau tidak puas. Karena itulah brosur atau selebaran jadi pilihan sebagai sarana perjuangan.
Ketika para siswi muslim dikenai kewajiban harus pindah ke sekolah-sekolah berlabel Islam hanya karena mereka tidak bersedia melepas jilbab, kami pun ikut sibuk menghubungi sekolah-sekolah Islam seperti perguruan Muhammadiyah, agar sejumlah siswi malang tersebut dapat diterima di sekolah-sekolah itu.
Bahkan ketika Alm. Amir Biki tertembak dalam peristiwa berdarah di Tanjung Priok pada 1984, kami diperintahkan mencari dan mewawancarai Faisal Biki, adik kandung Amir Biki yang waktu itu mengungsi atau bersembunyi di Bandung. Tujuannya, tentu saja, untuk mendapatkan informasi dari sisi korban dalam peristiwa berdarah pada malam jahanam itu, ketika informasi yang ada hanyalah dari satu sumber, yaitu pemerintah.
Natsir adalah idola bagi kalangan aktifis Islam tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di sejumlah negara sahabat. Banyak sekali aktifis muda Islam yang merasa begitu dekat dengan beliau, sehingga tidak sedikit yang memanggil beliau “abah”. Layaknya panggilan seorang anak kepada orang yang merupakan bapak biologisnya. Tetapi kami para karyawan DDII rata-rata memanggil beliau bapak, karena kami hanyalah orang-orang yang makan gaji di lembaga yang beliau pimpin. Meskipun cara berpikir kami terpengaruh oleh beliau, tapi kami tak merasa sepenuhnya menjadi anak ideologis, apalagi biologis.
*
SAYA AKUI, intro di atas terasa kepanjangan. Tapi memang begitulah, jadi kurang pas rasanya untuk dipersingkat. Sebab saya ingin menekankan bagaimana sosok seorang Natsir, terutama berkenaan dengan pandangan-pandangannya tentang “leadership” (kepemimpinan). Topik yang lagi hangat-hangatnya jadi buah bibir sebagian anak bangsa belakangan ini. Khususnya ketika penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta sudah tinggal menghitung hari. Ketika sebagian besar warga Jakarta yang pastinya adalah kaum muslimin akan menentukan pilihannya terhadap persoalan “leadership” Jakarta untuk lima tahun ke depan.
Natsir adalah salah seorang tokoh pergerakan bangsa yang terlibat polemik yang berulang-ulang dengan Proklamator Bung Karno, ketika hendak menetapkan dasar negara. Intinya, Natsir ingin memperjuangkan agar Islam dijadikan dasar negara di republik baru yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan Bung Karno tidak. Meski demikian, Bung Karno adalah seorang pemimpin bangsa yang “gentleman”.
Artinya, meskipun dia dalam beberapa hal berbeda pandangan sangat keras dengan Natsir, tapi dalam beberapa hal lain dia menaruh hormat kepada lawan debatnya yang paling tangguh itu. Karenanya Bung Karno tidak pernah menghalangi Natsir untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu, bahkan sampai menjadi Perdana Menteri.
 Mohammad Natsir (Foto: istimewa)
Mohammad Natsir (Foto: istimewa)
Menurut pandangan Bung Karno, demokrasi adalah system pemerintah yang paling tepat untuk dianut. Bung Karno misalnya memberi contoh pemerintahan Turki di bawah Kemal Attaturk adalah pemerintahan yang demokratis. Itulah pemerintahan yang terbaik, yang memisahkan agama dengan negara.
Tapi berbeda dengan Soekarno yang menganggap Turki demokratis pada masa pemerintahan Kemal, Natsir justru berpendapat Turki masa Kemal adalah pemerintahan diktator. Pada masa pemerintahan Kemal, kata Natsir, tidak ada kemerdekaan pers, kemerdekaan berpikir, dan kebebasan membentuk partai oposisi. Juga, Islam hanya ditoleransi untuk berkembang sejauh menyangkut aspek-aspek tertentu saja, Islam Im Schutzscahft. Tidak ada kemerdekaan bagi Islam di tanah Turki merdeka ....
Bung Karno membandingkan masa pemerintahan Kemal Attaturk dengan masa pemerintahan Khalifah Usmaniyah terakhir yang dianggap adalah sebuah pemerintahan Islam. Natsir dengan tegas menyatakan buruknya pemerintahan Kemal Attaturk seperti dijelaskan di atas. Sedangkan tentang kekhalifahan Usmaniyah terakhir, menurut Natsir, tidak bisa dijadikan patokan suatu pemerintahan Islam. Sebab kekhalifahan itu bukanlah pemerintahan Islam, sebab para pemimpinnya menindas dan membiarkan rakyatnya bodoh dengan memakai Islam dan segala bentuk ibadah-ibadahnya sebagai tameng belaka.
Semua itu, menurut Natsir, adalah kesalahpandangan Bung Karno dalam menjadikan sejarah sebagai sebuah fakta suatu pemerintahan Islam yang mesti dianut.
"Kalau kita terangkan, bahwa agama dan negara harus bersatu, maka terbayang sudah di mata mereka, bagaimana seorang bahlul (bloody fool) duduk di atas singasana, dikelilingi oleh "haremnya", menonton tari "dayang-dayang". Terbayang olehnya yang duduk mengepalai "kementerian kerajaan", beberapa orang tua bangka memegang hoga. Sebab memang beginilah gambaran 'pemerintahan Islam' yang digambarkan dalam kitab-kitab Eropa yang mereka baca dan diterangkan oleh guru-guru bangsa barat selama ini. Sebab umumnya (kecuali amat sedikit) bagi orang Eropa: Chalifah = Harem; Islam = poligami."
*
SEANDAINYA kita mau mempelajari lebih dalam bagaimana pandangan Natsir tentang negara dan pemerintahan yang mesti ditegakkan – dalam hal ini pastinya juga pemimpin yang mesti dipilih – akan semakin jelas bagi kita bahwa gambaran pemerintahan Islam sejauh ini, yang sangat ditakuti sebagian kalangan disebabkan kesalahfahaman mereka, sejatinya adalah pemerintahan yang menghambakan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dus, dengan demikian adalah pemerintahan yang mengikuti aturan bagi kebaikan untuk seluruh umat manusia, karena inilah sesungguhnya inti ajaran yang ditetapkan Allah Swt.
Sehubungan dengan itu, Natsir memagari pandangannya dengan mengutip nas Alquran yang dianggap sebagai dasar ideologi Islam, yang artinya, "Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada-Ku." (Alqur’an 51: 56). Bertitik tolak dari dasar ideologi Islam ini, ia berkesimpulan bahwa cita-cita hidup seorang Muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi hamba Allah, agar mencapai kejayaan dunia dan akhirat kelak.
Dengan demikian, sesuai pandangan Natsir, seorang pemimpin dalam Islam adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Swt., demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, baik bagi dirinya sendiri maupun umat yang dia pimpin. Seorang pemimpin itu adalah orang yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di akhirat kelak. Tergantung kepadanya apa yang akan dia pilih di antara dua: Masuk surga duluan atau menjadi orang yang paling awal dilemparkan ke dalam api neraka.
Dan bagi yang akan dipimpin, pilihannya lebih kurang juga sama. Apakah akan menjatuhkan pilihannya sesuai dengan ajaran Islam atau membiarkan dirinya hanyut menggapai impian duniawi yang penuh kepalsuan. Kalau mau berpedoman kepada ayat Alqur’an 51:56 di atas, jelaslah kemenangan haqiqi yang pasti anda raih. Sebab siapa yang anda pilih juga akan anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.
Kalau mau berpedoman kepada pandangan Natsir, beliau mengatakan, "Yang menjadi syarat untuk menjadi kepala negara Islam adalah, Agamanya, sifat dan tabiatnya, akhlak dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya. Jadi bukanlah bangsa dan keturunannya ataupun semata-mata inteleknya saja."
Warga Jakarta, Selamat berdemokrasi!