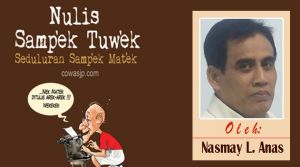COWASJP.COM – ockquote>
Sebuah artikel di Harian Kompas 9 Februari 2016 ditulis oleh budayawan Radhar Panca Dahana mengelu-elukan dan mengagungkan ketenangan bangsa Indonesia dalam menyikapi teror di Jl Thamrin, Jakarta beberapa waktu yang lalu. Radhar menyebut sikap tenang itu sebagai kematangan budaya. Saya melihatnya dari sisi yang berbeda.
O l e h: Dhimam Abror Djuraid
-------------------------------------------
TULISAN ini akan mencoba melihat peristiwa ini dari sisi yang berbeda. Ada empat gejala yang menjelaskan peristiwa teror Jl Thamrin, yaitu gejala banalitas kekerasan, gejala guncangan besar, gejala dramaturgi politik, dan gejala lemah karsa.
Reaksi masyarakat yang sangat tenang itu bisa menjadi indikasi bahwa masyarakat sudah kebal terhadap berbagai peristiwa kejahatan dan kekerasan yang terjadi setiap hari, baik itu kekerasan kriminal maupun kekerasan hidup yang mereka alami setiap hari. Masyarakat menganggap kekerasan atau kejahatan sebagai sesuatu yang biasa, karena mereka menyaksikan atau mengalaminya setiap hari.
Ketenangan sikap ini beda tipis dengan keacuhan, ketidakpedulian terhadap keadaan sekitar. Pola hidup individual sebagai akibat kondisi sosial kehidupan yang keras mengakibat perubahan besar dalam pola hubungan masyarakat. Kerekatan dan kepedulian sosial berubah menjadi keacuhan dan ketidakpedulian.
Sikap tenang masyarakat itu lebih terlihat sebagai sikap acuh karena menganggap peristiwa teror itu tidak lebih dari dagelan politik sebagaimana yang mereka saksikan di Senayan dan juga dalam perseteruan di antara parpol yang tidak kunjung ada habisnya. Masyarakat menonton adegan teror itu seperti menonton pengambilan gambar sinetron. Andai saja keributan yang terjadi di gedung DPR
Senayan bisa ditonton masyarakat secara langsung, pasti masyarakat akan berbondong-bondong menyaksikannya sambil berjualan makanan dan berselfie seperti yang mereka lakukan di Jl Thamrin.
Ketenangan masyarakat itu ljuga bisa menjadi indikasi kelemahan motivasi (karsa) untuk bergerak maju. Sikap apatis, menerima apa adanya, tidak peduli dengan keadaan sekitar, dan pasrah terhadap masa depan adalah sikap lemah karsa yang muncul akibat kesalahan interpertasi terhadap doktrin takdir dalam agama.
BANALITAS KEJAHATAN
Ketika kejahatan dan kekerasan terjadi secara sistematis dan terus-menerus maka akan muncul kekebalan pada masyarakat. Mereka tidak lagi mempunyai kepekaan dalam melihat kejahatan. Akibatnya, pada titik tertentu masyarakat bisa saja melakukan kekerasan dalam skala besar, meskipun pada dasarnya mereka bukanlah orang yang jahat.
Hannah Arendt menyebut hal ini sebagai ‘’Banality of Evil’’ atau banalitas kejahatan. Menurut Arendt kejahatan struktural yang dilakukan secara sistematis oleh negara terhadap warganya akan membuat warga kebal terhadap kejahatan itu dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Pada titik selanjutnya masyarakat bisa melakukan kekerasan besar karena menanggapnya sebagai sesuatu yang biasa.
Rieke Diah Pitaloka (2000) memakai teori Arendt itu untuk menggambarkan rezim otoritarian Orde Baru. Menurut Pitaloka, rezim Orde Baru telah melakukan kejahatan politik yang sistematis terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengalami banalitas kejahatan dan menganggap kejahatan negara itu sebagai bukan kejahatan. Pada sebuah titik akhirnya masyarakat melakukan kekerasan komunal sebagaimana yang terjadi dalam beberapa tindak kekerasan di awal masa Reformasi, misalnya di Sampit.
Banalitas kejahatan terjadi ketika seseorang merasa biasa saja ketika melihat kekerasan terjadi di sekeliling mereka. Kejahatan itu bisa dalam skala besar, bisa juga dalam skala yang lebih kecil misalnya pemalakan, pencurian, penjambretan, dan sejenisnya.
Mengacu kepada Arrendt, sikap ini terjadi karena masyarakat sudah terbiasa melihat kekerasan atau sudah terbiasa menerima kekerasan hidup. Ibarat ‘’teori kakus’’, ketika kali pertama masuk ke kakus seseorang akan menutup hidung karena baunya. Lama kelamaan dia akan bernapas seperti biasa karena menganggap bau itu sebagai hal yang biasa.
GUNCANGAN BESAR
Francis Fukuyama (2000) mengungkap fenomena ‘’Great Disruption’’ (guncangan besar) karena perubahan sosial yang besar akibat berbagai kebijakan pembangunan yang salah desain. Kebiajakan ekonomi yang melahirkan disparitas kesejahteraan menjadi salah satu penyebab guncangan besar. Perubahan hubungan keluarga yang renggang antara orang tua dengan anak melahirkan guncangan besar. Munculnya kebebasan pergaulan di kalangan anak-anak muda juga menjadi sumber guncangan besar.
Sebuah tata kota yang keliru akan berkorelasi dengan meningkatknya tingkat kriminalitas dan sensisifitas masyarakat terhadap kekerasan dan kejahatan. Sebuah tata perumahan yang terbuka yang memungkinkan anggota masyarakat saling sapa dan berinteraksi akan melahirkan kerekatan sosial yang tinggi. Sebaliknya perumahan dengan pagar tinggi dan portal besar dilengkapi dengan sekuriti 24 jam akan melahirkan gated community dimana kerekatan sosial yang lemah melahirkan kepedulian sosial yang tipis yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kriminalitas.
Polal hubungan masyarakat paguyuban atau gemeinschaft , dalam terminologi Ferdinand Tonnies, lebih responsif terhadap kejahatan di sekitarnya. Pola hubungan patembayan, geselschaft yang lebih individual akan melahirkan sikap yang kurang responsif terhadap kejahatan di sekelilingnya. Sikap individualistis masyarakat Indonesia, terutama yang kita saksikan di ibukota akan melahirkan sikap yang tidak peka terhadap kejahatan.
Ancaman terbesar dari guncangan sosial ini adalah terkikisnya modal sosial (social capital) yang sangat penting untuk merekatkan masyarakat. Modal sosial yang kuat akan melahirkan ‘’high trust society’’, masyarakat yang mempunyai tingkat saling percaya tinggi, sebagai lawan dari ‘’low trust society’’ atau masyarakat dengan tingkat saling percaya yang rendah. Pada hight trust society masyarakat akan saling peduli terhadap hal-hal kecil yang terjadi di sekitarnya. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat saling percaya yang rendah akan saling mengacuhkan satu dengan lainnya dan saling tidak peduli terhadap apa yang terjadi dengan lainnya.
DRAMATURGI
Teror di Jalan Thamrin menjadi tontonan masyarakat seperti menonton pengambilan gambar sinetron. Secara harfiah masyarakat menganggap peristiwa itu seperti sebuah sinetron, kalau tidak sebuah dagelan. Apa yang terjadi di Jalan Thamrin dianggap sebagai bagian dari rangkaian cerita yang terkait dengan lainnya. Ibarat sebuah tontonan, Jalan Thamrin adalah tontonan di ‘’panggung depan’’ yang bisa disaksikan secara terbuka oleh masyarakat.
Di balik panggung terbuka itu ada ‘’panggung belakang’’ yang tidak bisa ditonton oleh masyarakat. Di panggung belakang itu terjadi ‘’power play’’ permainan kekuasaan melibatkan para politisi, presiden, wakil presiden, Kapolri, Kepala BIN, atau aktor-aktor politik lainnya yang saling sikut, saling sodok, saling seruduk untuk berebut kekuasaan.
Inilah yang oleh Erving Goffman (1955) disebut sebagai ‘’Dramaturgi’’, sebuah adegan kehidupan pribadi dan sosial maupun politik yang mengenal dua panggung ‘’front stage’’, panggung depan, dan ‘’back stage’’, panggung belakang. Dalam kehidupan sehari-hari orang memainkan dua peran yang berbeda ketika berada di panggung depan dan ketika berada di panggung belakang. Di panggung depan orang akan memainkan peran sebagai ‘’Me’’ atau ‘’aku objek’’ yang harus bertindak sesuai dengan tata aturan dan sopan santun yang diatur oleh masyarakat. Aku objek menjaga citra diri atau jaga imej (jaim). Inilah yang oleh George Herbert Mead disebut sebagai ‘’the looking glass self’’ ketika seseorang harus berakting sesuai peran yang diberikan oleh mata orang lain atau mata masyarakat. Di panggung belakang orang akan memainkan dirinya sendiri yang asli yaitu ‘’I’’ aku subjek, yang menampakkan wajah dan karakter asli orang tersebut.
Di dunia sosial dan politik, para aktor itu setiap hari memainkan peran ganda di panggung depan dan panggung belakang. Apa yang terjadi di panggung depan bisa bertolak belakang dengan apa yang dimainkan di panggung belakang. Teror Jalan Thamrin adalah episode kecil di panggung depan yang bisa ditonton oleh masyarakat. Para teroris itu hanyalah pemain figuran yang memainkan peran kecil. Sementara di balik itu ada aktor-aktor kakap yang memainkan peran besar, dan ada juga sutradara besar yang menyusun skenario dan mengatur pertunjukan. Apa yang terjadi di panggung belakang jauh lebih rumit, penuh intrik, dan jauh lebih menarik untuk disaksikan. Sayangnya masyarakat tidak bisa menyaksikan secara langsung. Karena itu yang muncul adalah spekulasi, desas-desus, gosip, dan sejenisnya.
LEMAH KARSA
Lemah karsa adalah gejala kehilangan motivasi untuk maju akibat kejumudan berpikir yang muncul karena misinterpretasi paham keagamaan. Herman Soewardi (1999) menyebutkan beberapa indikasi lemah karsa, antara lain, tidak ada orientasi kedepan, tidak ada ‘’growth filosophy’’ kesadaran pikiran untuk tumbuh berkembang, tidak tangguh dan cepat menyerah, eskapisme/retreatisme atau kecenderungan untuk kembali ke akhirat, dan lambat bereaksi atau inertia.
Gejala-gejala ini muncul karena sejarah panjang bangsa Indonesia sejak masuknya Islam sampai masa penjajahan dan berlanjut hingga sekarang. Masa penjajahan yang panjang dan penuh penderitaan menyebabkan bangsa Indonesia menderita lemah karsa. Agama kemudian dijadikan pelarian untuk mencari perlindungan. Paham yang mendapat pengikut luas adalah pemahaman bahwa semua kesulitan hidup ini adalah ujian di dunia yang harus dihadapi dengan tawakal, karena nanti akan mendapatkan ganjaran besar di akhirat. Paham ini sering menimbulkan sikap fatalisme yang mengakibatkan lemah karsa yang parah.
Semua kesulitan hidup dihadapi dengan ‘’tabah’’ karena dianggap sebagai ketentuan Tuhan (takdir) yang tidak bisa diubah apalagi dilawan. Tidak ada keyakinan bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengubah nasibnya sendiri. Yang muncul adalah sikap pasrah menerima nasib dan menggantung harapan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik di akhirat. Apa yang terlihat pasca teror Jalan Thamrin adalah kelemahan karsa karena sikap yang jumud, tidak peduli, dan pikiran yang pasrah, dan sikap ‘’apa yang terjadi terjadilah’’.
TETAP OPTIMISTIS
Ruang untuk tetap optimistis bagi perbaikan bangsa kita kedepan masih sangat terbuka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fukuyama, guncangan besar telah melahirkan perubahan sosial besar yang mengkhawatirkan. Tetapi, ia tetap optimistis bahwa perubahan besar ini akan melahirkan tatanan sosial baru yang lebih baik. Salah satu syaratnya adalah modal sosial harus tetap kuat, dan ini bisa ditumbuhkan melalui pembentukan norma sebagai hasil dari interaksi intensif antar-masyarakat.
Fukuyama mengenyampingkan peran pemerintah untuk menumbuhkan modal sosial melalui pembentukan norma ini. Sebaliknya, ia selalu konsisten untuk memberi peran yang lebih besar kepada masyarakat. Pembentukan norma, salah satunya, adalah melalui pembentukan organisasi sosial yang bersifat sukarela (voluntir) dan sosialisasi nilai-nilai agama. Bangsa Indonesia mempunyai modal yang lebih dari cukup untuk melakukannya.
Bangsa Indonesia juga sudah semakin pintar menyikapi perkembangan politik. Mereka bisa membedakan mana yang dagelan dan mana yang serius. Masyarakat sudah tahu mana panggung depan dan mana panggung belakang. Para politisi dan penyelenggara negara harus menyadari hal ini. Kalau tidak, mereka akan ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap tak lebih dari badut politik.
Kelemahan karsa bangsa Indonesia berakar dari pemahaman agama yang kurang sesuai dengan era modern sekarang ini. Pada titik inilah diperlukan revolusi mental untuk mengembalikan karsa lemah menjadi karsa yang kuat. Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia memainkan peran yang penting dalam revolusi mental ini. Pemahaman terhadap sejarah dan doktrin Islam yang benar akan bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Sejarah Islam pada abad ke-7 sampai 14 menunjukkan bahwa Islam yang dipahami dan dijalankan dengan benar bisa menjadi kekuatan yang bisa mengubah sejarah. Api Islam inilah yang harus kita gali untuk menuju Indonesia yang lebih baik. (*)
Catatan: Artikel ini saya kirim ke kompas tapi tidak dimuat, akhirnya ya saya kirim ke cowasjp.com saja.