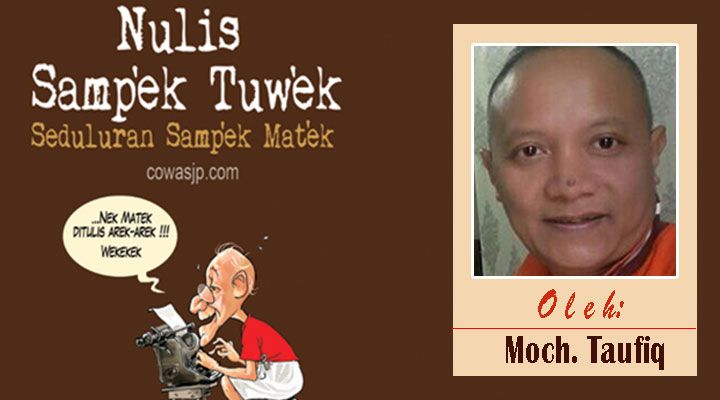COWASJP.COM –
SAYA tak mengenal Dahlan Iskan secara dekat, selama saya bergabung dengan Jawa Pos sejak 1988, dan kemudian ditugaskan di tabloid NYATA, KOMPETISI, WANITA INDONESIA (supervisi), JPNN, dan majalah LIBERTY. Dan, saya juga merasa tidak termasuk anak-buahnya yang dilirik ‘lebih’, sebagaimana dilakukan Bos –demikian saya biasa memanggil Dahlan Iskan—terhadap beberapa orang rekan saya di Jawa Pos. Namun, saya tetap merasa bahwa Bos memiliki kepekaan khusus terhadap pegawainya., termasuk saya.
Terus-terang –tetapi jangan bilang-bilang, ya, ke Bos—saya mungkin satu-satunya wartawan di Jawa Pos Grup yang paling ‘takut’ berhadapan langsung dengan beliau. Bukan ‘takut’ dalam arti yang sempit, melainkan ‘takut’ sebagaimana santri kepada gurunya di sebuah pondok pesantren tradisional di dusun nun jauh di sana.
Saya sangat menaruh hormat dan kagum atas kehebatannya mengelola bisnis media. Meskipun saya tahu ada beberapa anak perusahaan Jawa Pos yang babak-belur dan kemudian gulung-tikar, namun di mata saya apa pun yang disentuh Bos, selalu berubah menjadi emas. Dia benar-benar teladan bagi orang seperti saya yang selalu ingin maju dengan modal yang sangat pas-pasan.
Jadi, saya sering salting dan grogi –sekali lagi jangan dibocorkan ke Bos, ya-- setiap kali berhadapan dengan beliau. Terhadap pimpinan lain di Jawa Pos, saya biasa-biasa saja. Saya selalu hormat kepada mereka, tetapi saya tidak takzim, sebagaimana sikap saya kepada Bos.
Meskipun kelihatan cuek terhadap pegawainya, namun Bos sering memberi kejutan kepada pegawainya yang dinilainya memiliki nilai khusus. Nilai khusus yang dimaksud di sini, bisa diartikan bandel atau sebaliknya: cukup berprestasi.
Ketika saya masih menjadi Redaktur Pelaksana di NYATA, misalnya, Bos menegur pernah 2 kali menegur saya. Teguran pertama kira-kira berisi pujiannya, karena oplah NYATA menembus angka 80 ribuan eksemplar berkat promosi dalam Ketoprak Sayembara di Solo. Teguran kedua,”Oplah NYATA-mu sudah bagus. Tapi, hurufnya banyak yang salah. Malu dibaca orang.”
Dua teguran tersebut sungguh mengejutkan saya. Sebab, saya tidak pernah berkomunikasi dengan beliau. Baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun pegawainya. Saya hanya membatin, ternyata diam-diam Bos memperhatikan kualitas pekerjaan anak-buahnya. Meskipun sempat malu karena dikoreksi tentang banyaknya huruf yang salah, namun waktu itu saya sempat tersenyum nakal, dan ge-er sendiri. “Bos tahu banyak huruf yang salah, karena baca gosip-gosip artis di NYATA. Hmmmh... rupanya Bos hobi juga, ya, ngikutin berita miring artis kita.”
Bukan bermaksud untuk nge-cap atau menyombongkan diri, ya. Namun, waktu itu –sekitar akhir tahun 90-an—NYATA termasuk tabloid lokal yang telah diperhitungkan oleh media cetak sejenisnya di Ibukota, karena isu-isu hangat artis Jakarta. Menariknya, kantor redaksi NYATA tidak punya komputer sama sekali. Saya dan Rass Poerwanto (lay-outer) selalu menumpang komputer milik redaksi Jawa Pos. Kalau redaktur dan lay-outer Jawa Pos mulai masuk kantor menjelang sore hari, saya harus angkat kaki. Lha, namanya juga menumpang!
Teguran yang mengejutkan dari Bos datang lagi. Kali ini bahkan sangat mengejutkan saya. Suatu siang, pas saya sedang duduk di depan komputer redaksi lama Jawa Pos di Jalan Prapanca Raya 40 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tiba-tiba saja Bos sudah berdiri di samping kanan saya. Yang mengagetkan saya, Bos langsung membicarakan nasib saya di NYATA yang terkatung-katung, pasca saya ditugaskan ke Jakarta tanpa alasan dan job yang jelas.
“Ya, Bos...,” kata saya, deg-degan. Pikir saya,”Ada apa ini, kok nggak ada angin dan hujan, tahu-tahu Bos muncul di sebelah saya?”
“Saya sudah bilang tentang kamu....”
Maaf, kalimat Bos yang lainnya tidak perlu saya lanjutkan. Nggak penting. Namun, yang lebih penting adalah saya ‘dipulangkan’ kembali ke Surabaya. Saya juga purnatugas di NYATA. Lebih dari sebulan saya luntang-lantung di kantor Jawa Pos, Jalan Karah Agung 45 Surabaya. Tak ada job apa pun untuk saya, hingga akhirnya saya ditugaskan untuk memperkuat KOMPETISI sebagai redaktur pelaksananya. Ketika itu KOMPETISI dipimpin Nadim Zuhdi (almarhum). Selain saya, posisi redaktur pelaksananya juga dijabat oleh Hadi Wirawan (mantan wartawan olahraga andalan Surabaya Pos).
Tidak lama saya di KOMPETISI, saya ditugaskan Bos untuk membantu Wanita Indonesia-nya Mbak Tutut di Jakarta. “Ada konflik di redaksinya. Kamu bantulah Pimred-nya.”
Selama 4 bulan saya di Wanita Indonesia, hingga akhirnya saya pulang lagi di Surabaya. Kembali saya tak punya job apa-apa. Ini berlangsung 3 bulan.
Kemudian saya diminta bergabung dalam tim redaksi (sementara) JPNN, bersama Sam Abede Pareno dan Bambang Hariawan (mantan wartawan senior di Surabaya Pos). Kami bertiga bertugas untuk mensuplai berita-berita ke seluruh anak perusahaan Jawa Pos di daerah. Mohon maaf, saya tidak dapat menyebutkan siapa yang memberi instruksi saya untuk ke JPNN. Maklum, sudah lupa... haa...haa...
Belum genap 3 bulan saya membantu Pak Sam dan Mas Bambang di JPNN, tiba-tiba muncul yang mengejutkan dari Bos. Kali ini kejadiannya pada malam hari, tepat di ruang resepsionis kantor redaksi Jawa Pos.
“Taufiq, kamu sekarang di mana?” tanya Bos. Kayaknya dia baru saja masuk lobi kantor.
“Saya bantu-bantu Pak Sam dan Mas Bambang di JPNN, Bos,” jawa saya.
“Oke.. kamu ke LIBERTY saja. LIBERTY sekarang perlu bantuan.”
“Ya, Bos,” jawab saya, sambil manggut-manggut. Secara umum saya tahu konten LIBERTY pada waktu itu. Tetapi, justru yang jadi persoalan adalah redaksi LIBERTY penuh dengan senior saya sebagai jurnalis. Beberapa orang di sana adalah senior saya, ketika saya baru mengawali karier sebagai wartawan pada usia 17 tahun. Just info saja, saya mulai bekerja sebagai wartawan magang, ya, di LIBERTY itulah. Ketika itu LIBERTY tampil sebagai mingguan berita.
Redaktur Pelaksananya: Anshari Thayib (almarhum) dan Enong Ismail (kini kurator lukisan di Bali). Pemimpin Redaksinya: Goh Tjing Hok. Saya baru naik kelas 2 SMA Negeri 8 Surabaya. Sepulang sekolah di pagi hari, saya magang sebagai reporter di sana.
“Jadi, LIBERTY diapain, Bos?” tanya saya, polos. Maaf, polos atau o’on, ya, Pembaca?
“Nggak tahu. Pokoknya harus lebih untung,” jawab Bos, sambil ngeloyor begitu saja.
Tetapi sebelum ngeloyor, sesungguhnya Bos kembali memberi kejutan lagi ke saya. “Kamu punya paspor, kan?”
“Belum, Bos?”
“Lho....? Kalau begitu, besok kamu urus ke Mbak Oemi. Kamu ikut saya ke Hong Kong. Minta tolong ke Nasaruddin untuk urus paspornya.”
Saya melongo. Jujur saja, sebenarnya saya nggak suka ke Hong Kong (HK). Saya nggak pede, karena saya pasif berbahasa Inggris. Itu pula sebabnya saya tidak pernah komplain atau mempersoalkan, kenapa saya tidak pernah sama sekali mendapat jatah ke luar negeri. Padahal kru lain di Jawa Pos --bahkan di non-redaksi yang di level rendah pun-- sudah merasakan indahnya pelesiran ke luar negeri dengan biaya perusahaan. Waktu itu saya pasrah saja.
Ibarat anak ayam, saya terlanjur merasa tidak punya induk. Tidak ada yang peduli terhadap saya.
Jadi, ya sudah... biarkan saja tidak ada yang ngurusin saja. Yang penting saya tetap gajian, begitulah pikiran saya waktu itu.
Eh, ternyata Bos –yang notabene pemilik Jawa Pos—sendiri lah yang ngurusin saya. Ketika di dalam pesawat menuju bandara Changi –dulu perlu transit dulu ke Singapura, sebelum terbang ke HK-- saya baru tahu bahwa saya dan Bos pergi ke HK untuk sebuah lokakarya bisnis media cetak se-Asia. Selain saya dan Bos, beberapa pemimpin redaksi koran top di Ibukota ikut dalam rombongan Indonesia ke forum tersebut. Selain Jawa Pos, koran dari daerah yang mengirimkan wakilnya hanyalah Bambang Sadono saja. Saat itu dia menjabat Pemimpin Redaksi Suara Merdeka (Semarang).
Selama di HK, saya baru benar-benar merasakan jiwa kebapakan Bos. Saya diajaknya bicara tentang masa depan percetakan modern Jawa Pos yang kelak dibangun di Graha Pena. Saya ditraktirnya makan bebek Peking yang nimat di sebuah restoran bergengsi. Menariknya lagi, uang sisa pembayarannya diberikan begitu saja ke saya. Jika dirupiahkan (tahun 1998), nilainya hampir Rp 400 ribu. Saya juga diberi Bos sebuah sweater.
“Pakailah. Saya baru beli di sini,” kata Bos, sambil menjulurkan sweater warna biru dongker.
Saya tahu, Bos tidak tega melihat saya tanpa jaket, sweater atau jas selama di HK. Waktu itu, di bulan Desember, cuaca HK memang lagi dingin. Dia sempat bertanya ke saya,”Kamu nggak bawa jas?”
Saya menggelengkan kepala. “Boro-boro jas,” batin saya. “Dasi saja saya nggak punya, Bos.”
Di hari pertama lokakarya –tepatnya beberapa menit sebelum acara dimulai-- saya mendapat teguran lagi dari Bos. Waktu itu dia sudah duduk di barisan terdepan yang diperuntukkan peserta lokakarya.
Saya memutuskan untuk duduk di barisan ke-4. Ada 21 barisan lagi di belakang saya. Saya berpendapat, bahwa saya masih berada di barisan utama. Masih di barisan depan.
“Taufiq, sini!” panggil Bos.
Sigap saya mendekatinya. “Ya, Bos...”
“Duduk di sini.... di sebelah saya.”
Begitu pantat saya sudah menempel di kursi barisan terdepan, Bos langsung berkomentar,”Gimana kamu bisa jadi orang nomor satu, kalau pilih duduk di belakang saja.”
Deg..... kali ini saya benar-benar dibikin KO. Saya jadi malu sendiri.
Singkat cerita, saya sudah aktif menjadi redaktur pelaksana di LIBERTY. Alhamdulillah, majalan tersebut mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hingga pada suatu hari saya kembali ditegur oleh Bos. Kami bertemu secara tidak sengaja pada suatu siang, di kantor redaksi Jawa Pos di Jalan Karah Agung 45. Sementara kantor LIBERTY terletak di Jalan Pahlawan.
“Taufiq, kamu jangan ikut-ikutan nggak bikin event untuk LIBERTY. Kamu, kan pimpinan. Jangan ikut-ikutan anak-buahmu.”
Saya sungguh terkejut. Darimana Bos tahu masalah internal di LIBERTY, sedangkan saya tidak pernah cerita apa pun ke dia. Setelah saya menjelaskannya secara sederhana, beliau langsung manggut-manggut. “Ya, kamu nggak salah. Nggak apa-apa,” katanya, sambil menepuk pundak kanan saya.
Dua tahun kemudian, tiba-tiba saja Bos menelepon saya. Waktu itu saya masih berada di ruang kerja saya. Koesnan Soekandar, bos saya di LIBERTY yang seruangan dengan saya, sedang tidak ada di kursinya.
“Benar kamu mau keluar?” tanya Bos dari seberang sana.
“Iya, Bos,” jawab saya.
“Kenapa?”

Dahlan Iskan (Foto:manadopostonline)
“Nggak ada apa-apa, Bos.”
“Beneran?”
“Iya, Bos.”
“Ya, sudah kalau begitu.”
Saya tak tahu, apa yang ada di benak Bos kala itu. Saya pun tidak memusingkannya. Saya hanya merasa tidak nyaman lagi bekerja di sana. Karena saya tidak mau menyusahkan Bos, maka saya pilih hengkang saja. Biarlah perusahaan memilih pengganti saya. Toh, masih banyak orang lain yang memiliki kemampuan lebih dari saya. Biarlah waktu yang akan menjelaskan, kenapa saya mengambil sikap tersebut.
Sekian tahun kemudian, saya kembali harus berurusan dengan Bos. Namun, kali ini benar-benar menyangkut masalah pribadi saya. Itulah sebabnya saya menilai tidak pas jika isi pembicaraan saya dengan Bos –yang kami lakukan di dalam mobilnya—ditulis di website ini.
Nah, beberapa pekan terakhir ini saya kembali dikejutkan oleh Bos. Bukan karena tegurannya lagi, tetapi lantaran kasus hukum yang tengah membelit seorang Dahlan Iskan. Terus-terang saya benar-benar prihatin atas kondisi tersebut. Saya tahu integritas kejujurannya dalam bekerja.
Namun, saya sangat meyakini bahwa Bos bukanlah lelaki yang sama seperti saya yang ‘penakut’ itu.
Jadi, sekarang saya memutuskan untuk menunggu kejutan lagi dari Bos, sebagaimana yang pernah dia lakukan terhadap saya, atau pegawainya yang lain. Saya benar-benar berharap Bos kembali bergerak lincah dengan langkah-langkah ‘ajaib’-nya yang selama ini saya kagumi. Biarlah Allah yang menganugerahkan bagi dia.
Tetapi, maaf, ya Pembaca yang budiman. Masalah ini jangan dibocorkan ke Dahlan Iskan!
+++++
Surabaya, 4 November 2016