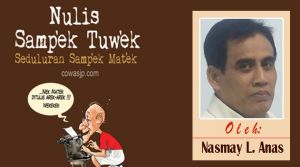COWASJP.COM – ockquote>
Suhu politik Jawa Timur mulai memanas menjelang pemilihan gubernur 2018. Beberapa nama kandidat mulai bermunculan. Persaingan keras dan ketat mungkin terjadi. Muncul gagasan membentuk ‘’Koalisi Jatim’’. Apa itu?
PEMILIHAN umum kepala daerah (Pemilukada) Jawa Timur akan dilakukan serentak pada 2018 dengan melibatkan 18 kabupaten kota untuk memilih walikota/bupati, dan satu pilkada untuk memilih kepala daerah provinsi (gubernur).
Meskipun pelaksanaan pemilukada masih relatif jauh tetapi dinamika politik sudah mulai menghangat, terutama yang berkaitan dengan pemilukada provinsi jawa timur untuk memilih gubernur baru.
Dengan berakhirnya masa bakti Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2014-2019. Soekarwo-Saifullah Yusuf, akan muncul dinamika politik yang lebih hangat karena Soekarwo sudah dua periode memimpin Jawa Timur.
Wakil Gubernur Saifullah Yusuf sudah mengambil ancang-ancang untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jatim, dan sampai sekarang terlihat sebagai ‘’front-runner’’ (pelari terdepan) karena calon-calon yang lain masih belum secara resmi muncul atau dimunculkan.
Beberapa nama yang beredar di masyarakat maupun media masih bersifat spekulatif, seperti Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial RI), Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Masfuk (Mantan Bupati Lamongan 2 periode, sekarang Ketua DPW-PAN Jatim), Eddy Rumpoko (Walikota Batu), Kusnadi (Ketua DPD PDIP Jatim), Budi ‘’Kanang’’ Sulistyo (Bupati Ngawi), Suyoto (Bupati Bojonegoro), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), dan beberapa nama lainnya. (Lihat hasil survei Polltracking Indonesia)
Jawa Timur adalah provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 42 juta orang. Tetapi, provinisi ini selalu disebut sebagai barometer politik nasional yang selalu memegang peran sangat penting dalam memengaruhi peta politik nasional. Hal ini terjadi karena dinamika politik Jawa Timur sangatlah tinggi dan tingkat heteroginitas yang juga lebih tinggi dibanding Jawa Barat maupun Jawa Tengah.
Karena itu Jawa Timur tetap menjadi barometer perkembangan politik nasional, sehingga memunculkan adagium bahwa untuk memenangkan kontestasi politik nasional harus memenangkan Jawa Timur terlebih dahulu.
Perhelatan pemilukada DKI Jakarta yang baru saja usai menyisakan sejumlah persoalan yang merembet menjadi persoalan nasional yang sangat serius. Persaingan antara dua pasang kontestan pemilukada DKI menyebabkan munculnya isu-isu sensitif menggelinding menjadi bola salju yang tidak bisa dikendalikan.
Perdebatan dan persaingan politik pada pemilukada DKI berkembang terlalu jauh dan ditunggangi oleh berbagai pihak dengan berbabagi agenda dan kepentingan politik masing-masing.Isu-isu mengenai eksistensi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), falsafah negara Pancasila, dasar negara UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika menjadi perdebatan yang liar dan melibatkan saling klaim satu pihak untuk menjatuhkan pihak lainnya.
Pemilukada DKI akhirnya berlangsung tanpa ricuh dan berjalan mulus tanpa kekerasan. Tetapi luka yang tergores terasa sampai sekarang dan masih akan terasa sampai waktu yang lama. Pemilukada DKI juga menunjukkan bahwa isu-isu sensitif itu ternyata masih belum selesai dan masih tetap menjadi persoalan kebangsaan yang menjadi PR besar seluruh komponen bangsa.
Bahwa ‘’Empat Pilar Kebangsaan’’; NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika, adalah konsensus nasional yang harus dijaga bersama,, ternyata masih belum menjadi kesepakatan nasional. Masih ada pihak-pihak yang ingin memaksakan agenda yang berseberangan dengan nilai-nilai kosensus nasional itu.
Politik aliran yang berdasarkan pada pilihan agama dan faktor-faktor primordialisme yang menjadi indikator masyarakat politik tradisional, secara kasat mata terlihat di pemilukada DKI. Meskipun hal ini dibantah, tetapi kenyataan di lapangan dari hasil perolehan suara pemilu masing-masing kontestan, menunjukkan secara jelas pola kemunculan politik aliran ini.
Dalam masyarakat urban yang didominasi kelas menengah yang rasional, semestinya politik aliran tidak banyak diikuti karena masyarakat lebih cenderung melihat program politik daripada isu-isu primordialisme. Tetapi, dalam pemilukada DKI terjadi anomali politik karena gencarnya terpaan media konvensional dan media sosial yang menyebabkan isu-isu aliran mendapatkan perhatian yang sangat besar.
Harus diakui bahwa tidak mudah menghilangkan sama sekali gerakan politik aliran di Indonesia, karena kontur demografi Indonesia yang memang secara tradisional terbagi ke dalam aliran-aliran primordial dan agama itu. Tetapi, pengelolaan politik aliran yang sangat pragmatis dan cenderung mengorbankan pilar-pilar kebangsaan yang sudah menjadi konsensus nasional, adalah tindakan politik yang membahayakan eksistensi bangsa. Hal ini memicu keprihatinan yang luas dan membutuhkan komitmen politik besar untuk menyelesaikannya.
Kondisi Jawa Timur
Tidak bisa dipungkiri bahwa ada upaya-upaya untuk ‘’mengekspor’’ isu-isu pemilukada DKI ke Jawa Timur oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu. Hal bisa dimaklumi karena pentingnya posisi Jawa Timur dalam kontestasi politik nasional. Jika isu-isu SARA yang mewarnai pemilukada DKI bisa dihembuskan dan dikobarkan di Jawa Timur, maka untuk menjadikannya sebagai isu nasional dalam pemilu presiden 2019 akan lebih mudah.
Wacana ini sudah dicium oleh para elite politik dan masyarakat di Jawa Timur. Meski belum secara terang-terangan dimunculkan tetapi asapnya samar-samar sudah tercium. Karena itu, sebagai antisipasi, sudah mulai muncul gerakan agar isu-isu sensitif itu tidak sampai mengimbas ke Jawa Timur. Gerakan informal ini sudah mulai mengemuka dan mendapat sambutan yang sangat positif di kalangan elite politik dan masyarakat Jawa Timur.
Kondisi demografi politik Jawa Timur dan DKI memang berbeda. DKI adalah ibukota metropolitan dengan tingkat heteroginitas yang tinggi tetapi dengan tingkat kerekatan sosial yang relatif rendah. Tingkat pendidikan yang secara umum lebih tinggi dengan tingkat melek teknologi yang lebih besar menjadikan masyarakat DKI lebih dinamis dan canggih dalam mengelola informasi.
Ciri masyarakat modern patembayan (gesselschaft) yang mempunyai ketergantungan tinggi terhadap teknologi informasi sangat terlihat di DKI. Kondisi masyarakat urban (perkotaan) yang cair ini tidak menempatkan opinion leader (pemimpin opini) tradisional sebagai pembentuk opini. Ciri masyarakat kelas menengah urban adalah independen dalam mengambil keputusan dan tidak bergantung kepada opinion leader formal maupun informal dan tradisional.
Berbeda dengan kondisi masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar masih rural-based (berbasis masyarakat pedesaan) yang bersifat paguyuban (gemeinschaft), posisi para pemimpin tradisional dan informal--seperti para kiai, ulama, ustad/ustadah, guru mengaji, kepala suku, kepala desa, dan sejenisnya--sangatlah penting dalam menentukan pilihan politik.
Potensi munculnya politik aliran sangatlah besar di Jawa Timur karena besarnya peran para pemimpin tradisional dan informal itu. Secara historis, politik aliran lahir di Jawa Timur. Adalah antropolog Amerika Serikat, Clifford Geertz, yang melakukan penelitian di Jawa Timur pada 1953 di kota yang secara imajiner disebut sebagai Mojokuto (diyakini oleh para ahli sebagai Pare, Kediri). Hasilnya tertuang dalam buku klasik master piece ‘’The Religion of Jawa’’ (Agama Jawa), yang membagi masyarakat menjadi kategori santri, abangan, dan priyayi.
Santri adalah masyarakat beragama Islam yang taat menjalankan syariah dan tinggal di daerah perniagaan di perkotaan dan pesisir. Abangan adalah pemeluk Islam nominal yang hanya menjadi identitas di KTP tetapi tidak menjalankan syariah agama, dan priyayi adalah kelompok kelas menengah kota yang terdiri dari pegawai negeri dan pamong praja yang beragama Islam tetapi sangat dipengaruhi oleh sinkretisme kejawen.
Berdasarkan tiga kategori ini preferensi politik terbagi kepada tiga aliran politik besar, kalangan abangan berafiliasi kepada partai-partai nasionalis dan berbasis di daerah mataraman, kalangan santri berafiliasi kepada partai-partai religius yang berbasis di daerah mataraman, dan kalangan priyayi berafiliasi kepada partai-partai ‘’modern’’ yang berbasis pada masyarakat urban perkotaan.
Cikal bakal politik aliran sangat kental di Jawa Timur dan benturan antara kekuatan aliran ini sangat potensial terjadi di Jawa Timur. Jika benturan politik terjadi maka gesekan di level akar rumput (grass root) akan sangat rawan membawa pada kekerasan komunal yang destruktif. Ancaman terhadap keutuhan pilar-pilar kebangsaan jauh lebih besar di Jawa Timur dibanding daerah lain termasuk DKI Jakarta. Karena itu mutlak bagi komponen elite Jawa Timur untuk mencegah kerawanan politik yang terjadi akibat eksploitasi politik aliran yang pragmatis dan salah arah.
Koalisi Jatim
Dengan mempertimbangkan berbagai hal itu lalu muncul gagasan untuk membentuk ‘’Koalisi Jawa Timur’’. Wacana ini sudah mulai beredar di kalangan masyarakat politik Jawa Timur meskipun rumusan kongkretnya belum pernah diungkapkan. Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf menjadi salah satu tokoh yang gencar mengusung gagasan ini.
Secara umum gagasan dasar dari Koalisi Jatim adalah menciptakan situasi politik yang kondusif di Jawa Timur dengan tetap mengakomodasi dinamika dan mekanisme politik untuk mencapai hasil politik yang bisa melahirkan pemimpin politik regional yang didukung semua atau sebagian besar komunitas politik Jawa Timur.
Dalam sistem pemilukada Indonesia yang sangat terpengaruh oleh ide-ide liberal seperti ‘’limapuluh persen plus satu’’, ‘’suara mayoritas’’, ‘’voting’’ dan sejenisnya, tempat untuk mengakomodasi kearifan nilai bangsa seperti musyawarah mufakat menjadi sempit. Sejak munculnya orde reformasi 1998, sistem politik Indonesia secara perlahan namun pasti bergerak ke arah liberalisme dengan mengadopsi sistem demokrasi dan pemerintahan Barat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.
Masih menjadi perdebatan luas apakah demokrasi bersifat unievrsal atau partikular. Apakah prinsip demokrasi liberal Amerika Serikat dan Eropa bisa begitu saja diterapkan di Indonesia masih menjadi perdebatan panjang dan berilku.
Demokrasi Amerika dan Eropa pun mempunyai perbedaan yang cukup mencolok dalam penerapannya. Amerikalebih cocok dengan sistem dua kamar; Kongres dan Senat serta sistem presidensial yang kuat, sementara di Eropa masih banyak yang memadukan demokrasi dengan tradisi lokal terutama monarki.
Pertanyaannya sekarang mengapa Indonesia tidak mengembangkan sistem demokrasinya sendiri? Mengapa Indonesia menjadi lebih liberal dibanding negara-negara liberal Eropa dan Amerika?
Sederet pertanyaan filosofis itu membutuhkan perenungan panjang untuk menjawab. Tetapi, Indonesia sudah mempunyai sistem Demokrasi Pancasila yang lebih tepat untuk diterapkan di lingkungan masyarakat kita.
Tetapi, bangsa Indonesia sudah terpengaruh oleh labelisasi dan stigmatisasi yang akhirnya menyebabkan nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi dan kemudian dicampakkan. Prinsip musyawarah-mufakat yang menjadi ruh Demokrasi Pancasila dijauhi seperti sebuah alergi dan kemudian kita menjiplak sistem demokrasi lain yang kedodoran ketika diterapkan di Indonesia.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan bahwa musyawarah mufakat tidak haram selama mekanisme demokrasi tetap dijalankan. Jadi, meskipun masih sebatas wacana, kelihatannya gagasan Koalisi Jatim akan terus menggelinding dan menarik untuk dilihat ending-nya. (*)