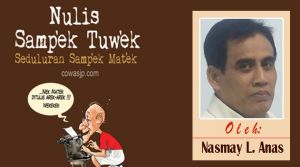COWASJP.COM – TIDAK gampang meminta maaf. Kelihatannya hanya urusan kecil tapi sungguh berat dilakukan. Meminta maaf bukan sekadar membuka bibir untuk mengucapkan kata maaf, tetapi juga membuka hati untuk mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dan mengakuinya. Salah dan khilaf adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia.
Bahkan kata ‘’manusia’’ dalam bahasa Arab (al-nas) mempunyai akar yang sama dengan kata alpa (naas). Maka pepatah Arab mengatakan ‘’Manusia adalah tempat salah dan lupa’’. Karena itu (seharusnya) tidak perlu malu untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf.
Tapi, kenyataannya tak semudah itu. Bagi kita manusia Indonesia, mengaku salah dan meminta maaf butuh keberanian ekstra, dan juga kejujuran yang ekstra. Karena itu, motto ‘’Berani Jujur itu Hebat’’ betul-betul hebat kalau betul-betul dijalankan oleh siapapun, termasuk yang membuat motto itu. Kalau pembuat motto itu sendiri malah tidak berani berbuat jujur (atau pernah tidak berbuat jujur tapi tidak jujur mengakuinya) maka yang terjadi adalah sandiwara, dagelan serba palsu.
Itulah Indonesia. Itulah watak bangsa kita.
Empat puluh tahun yang lalu, wartawan dan budayawan Mochtar Lubis dalam pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki menyebutan enam sifat buruk bangsa Indonesia antara lain munafik dan tidak mau bertanggung jawab. Pidato itu dilakukan pada 1977 dan kemudian dibukukan dan menimbulkan kontroversi seantero negeri. Tapi, sampai sekarang orang masih mengakui kebenaran tesis Lubis itu.
Budaya bangsa Indonesia tidak memungkinkan orang untuk berterus terang mengutarakan apa adanya. Kita lebih suka berputar-putar ngalor ngidul untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Bangsa Indonesia tidak mempunyai ‘’budaya rasa bersalah’’ (guilt culture). Yang kita punya adalah ‘’shame culture’’ atau budaya malu, dan budaya inilah yang mendasari sikap dan perbuatan kita dalam kehidupan.
 ILUSTRASI, Foto: istimewa/Desaing: CoWasJP
ILUSTRASI, Foto: istimewa/Desaing: CoWasJP
Kalau kita melakukan kesalahan--pribadi maupun sosial--kita tidak merasa bersalah, kita tenang-tenang saja. Kalau kita melanggar hak sosial orang lain, kita melanggar hak politik orang lain, kita melanggar dan merampas hak ekonomi orang lain, kita biasa-biasa saja dan tenang-tenang saja sepanjang perbuatan itu tidak diketahui orang lain.
Ketika kita menyetir kendaraan pada dinihari yang sepi dan menerobos lampu merah, kita merasa biasa-biasa saja. Tidak ada rasa bersalah apalagi berdosa, karena kita merasa tidak dilihat atau diketahui orang lain. Itulah bukti bahwa kita tidak mempunyai guilt culture.
Tapi, kalau seseorang kemudian terkena OTT maka kemudian dia akan menyembunyikan dirinya sedemikian rupa supaya tidak terekspos oleh media dan tidak diketahui oleh orang. Seseorang yang korupsi triliunan rupiah masih tetap cengengas-cengengas tidak merasa bersalah dan bahkan akan menggugat karena telah mempermalukannya. Itulah bukti bahwa kita kental dengan budaya shame culture.
Budayawan Umar Kayam (almarhum) mengatakan, korupsi di Indonesia amatlah rumit karena motifnya bukan sekadar urusan ekonomi tapi sudah bersilang sengkarut dengan masalah budaya. Kalau seseorang sudah dianggap sebagai orang sukses maka dia harus menjadi pengayom dan pembagi rezeki. Setiap kali si orang sukses membagi-bagi rezeki dia akan bangga karena telah memenuhi peran sosialnya.
Meski rezeki itu didapatnya dari jalan yang tidak halal tapi dia mendapatkan pembenaran dari perbuatannya. Dia tidak merasa bersalah atas tindakan memperoleh rezeki secara tidak halal itu. Karena itu sampai sekarang kita tidak pernah mendengar terpidana korupsi meminta maaf kepada siapapun karena telah melakukan korupsi.
Orang Eropa dan Jepang berbeda dengan kita karena mereka mempunyai ‘’guilt culture’’. Orang Barat akan merasa bersalah kalau melakukan pelanggaran dan tidak segan minta maaf, dan kalau dia punya jabatan publik dia akan mundur. Orang Jepang lebih seram lagi, kalau melakukan kesalahan mereka merasa bersalah dan tidak segan bunuh diri alias harakiri. Di Indonesia, jangankan minta maaf, malah KPK-nya dibubarkan.
Presiden Sukarno menyadari hal itu. Karenanya, dia ingin memberi contoh budaya politik yang lebih sehat. Dia mencari momentum untuk meminta maaf kepada kolega sesama politisi maupun kepada masyarakat secara luas sekaligus berupaya untuk melakukan rekonsiliasi nasional karena ada gejala disintegrasi. Atas saran KH. Wahab Chasbullah pada Idul Fitri 1948 Bung Karno mengumpulkan semua elite politik dalam sebuah acara di Istana dan saling meminta maaf. Acara itu sekarang dikenal sebagai Halal bi Halal.
Alangkah eloknya kalau Presiden kita sekarang meniru Sukarno dan mengadakan rekonsiliasi nasional serta saling meminta maaf secara tulus kepada semua elite politik dan masyarakat.
Ada saja yang mencibir, mengapa meminta maaf harus menunggu lebaran. Pertanyaannya sekarang, kapankah kali terakhir kita meminta maaf kepada keluarga, tetangga, kolega dan handai tolan? Kalau pada momentum lebaran saja enggan minta maaf apalagi pada momen lain. Karena itu, menfaatkanlah lebaran secara tulus ikhlas untuk minta maaf.
Di Indonesia, satu-satunya yang paling konsisten mempraktikkan budaya minta maaf adalah mesin-mesin ATM. Cobalah di tanggal tua ini datang ke mesin ATM dan masukkan angka tertentu, pasti jawabannya: Maaf, saldo Anda tidak mencukupi.....(*)