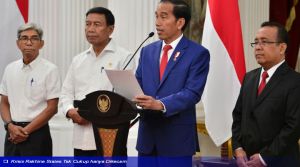COWASJP.COM – ockquote>
O l e h: Djoko Pitono
-----------------------------
Sinau basa, sinau bangsa. Sinau melu susah, melu sakit. Tegesipun: sinau ngudi raos lan batos. Sinau ngudi kamangnusan.
- Drs RMP Sosrokartono
KETIKA kasus-kasus berbau SARA (suku, agama, dan ras) bermunculan belakangan ini, nama KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) disebut-sebut banyak orang. Sebagian mereka mungkin membayangkan, seandainya mantan presiden kita itu masih hidup maka dengan mudah beliau akan mengatasi masalah. Nama Gus Dur adalah sebuah jaminan untuk perkara-perkara terkait dengan isu-isu sensitif seperti itu.
Oleh karena itu, ketika Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009, kepergiannya dilukiskan oleh berbagai kalangan sebagai kehilangan besar bangsa ini. Dalam upaya menghormati tokoh besar guru bangsa itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu menetapkan Gus Dur sebagai “Bapak Pluralisme”.
Gus Dur memang dikenal sebagai tokoh yang gigih memperjuangkan nilai-nilai pluralisme. Ia juga selalu berada di depan membela hak-hak kaum minoritas ketika mereka mendapat perlakuan diskriminatif. Semua itu menimbulkan risiko, mulai ancaman fisik hingga kecaman-kecaman pedas dan melecehkan. Tetapi Gus Dur tidak peduli.
Mungkin ada yang bertanya, dari manakah datangnya nilai-nilai pluralisme yang begitu melekat pada diri Gus Dur? Apakah jatuh dari langit begitu saja? Karena Gus Dur adalah “waliullah’ yang dikasihi oleh Yang Di Atas sana? Karena Gus Dur memiliki “kekuatan supranatural”?
Banyak orang telah menulis tentang Gus Dur, namun ada hal yang amat penting yang tampaknya terlupakan. Apa yang terlupakan itu utamanya menyangkut poliglotisme alias kemultibahasaan Gus Dur. Penguasaan Gus Dur dalam beberapa bahasa asing, yang ditopang oleh kebiasaannya yang sangat kuat dalam membaca buku, telah membuat santri asal Jombang, Jawa Timur, itu dapat memahami benar berbagai kebudayaan di luar masyarakatnya.
Informasi dari kerabat dan kawan-kawan dekatnya serta referensi buku-buku yang penulis gali menunjukkan, Gus Dur setidaknya sangat menguasai bahasa Inggris dan Arab. Pada tahap tertentu, Gus Dur juga memahami secara pasif bahasa Ibrani, Belanda, Jerman, dan Prancis. Penguasaannya dalam bahasa-bahasa itu bahkan sangat canggih. Satu ketika saat berbicara dengan Raja Arab Saudi, Fahd, Gus Dur mampu membuat sang raja tertawa terbahak-bahak hingga gigi Raja Fahd pun kelihatan. Tak pernah hal demikian terjadi, begitu laporan-laporan pers.
Kali lain, Gus Dur juga bisa membuat Presiden Bill Clinton dan Presiden Kuba Fidel Castro terpingkal-pingkal. Tak mungkin Gus Dur mampu membuat suasana demikian tanpa penguasaan bahasa yang luar biasa. Koleksi buku-bukunya dalam beragam bahasa amat banyak.
Seperti diketahui, Gus Dur pernah belajar di Universitas Al Azhar, Kairo, dan Universitas Baghdad, Irak.
Setelah itu, beliau juga pernah menetap beberapa waktu di Belanda, Jerman, dan Prancis.
Selama di Baghdad, Gus Dur disebut mempunyai seorang teman dekat sesama mahasiswa Universitas Baghdad, seorang pria Yahudi Irak. Keduanya berkawan akrab, hingga Gus Dur pun belajar bahasa Ibrani dan budaya Yahudi. Bahkan, dalam batas tertentu, Gus Dur juga belajar hal-hal mistik masyarakar Yahudi pada temannya itu. Inilah salah satu kunci penting mengapa Gus Dur dapat diterima oleh masyarakat dan para tokoh negara Yahudi tersebut. Jauh sebelum jadi Presiden, Gus Dur telah beberapa kali berkunjung ke Israel.
Ketika Gus Dur menjadi Presiden, salah satu rencana yang disampaikan adalah menjalin hubungan dengan Israel. Reaksi keras segera bermunculan dari berbagai pihak, terutama kalangan wakil rakyat alias DPR. Gus Dur dikecam sebagai pemimpin yang mengkhianati perjuangan rakyat Palestina yang dijajah Israel. Padahal, bila kita mau jujur, kita bisa mempertanyakan “bantuan” dunia Islam khususnya lagi negara-negara Arab kepada rakyat Palestina selama ini. Terlalu gegabah bila kita mengatakan bahwa selama ini tidak ada bantuan kepada rakyat Palestina. Tetapi jelas tidak maksimal, karena buktinya rakyat Palestina terus menderita. Sebagian negara Arab pun saling bermusuhan sendiri sampai sekarang, bahkan lebih menyedihkan.
Dalam penyelesaian sengketa Israel-Palestina, penulis melihat Gus Dur ingin melakukan pendekatan secara halus – dengan menohok hati – para pemimpin Israel. Sayang sekali Gus Dur tidak mendapat kesempatan yang lebih panjang. Bisa dirasakan, Gus Dur ingin sekali menaklukkan Israel dengan pepatah Jawa “ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake”. Mungkin ada yang tertawa membaca ini.
Tetapi dalam konteks budaya, pepatah tersebut benar-benar hebat. Gus Dur benar-benar ingin menaklukkan Israel lewat pendekatan budaya sehingga negara Yahudi tersebut bersedia menerima berdirinya negara Palestina. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar – yang sangat toleran – adalah jaminan bagi Israel. Sudah jauh sejak lama Israel ingin menjalin hubungan dengan Indonesia.
Dalam konteks sejarah Islam pun ada kisah yang relevan bagaimana Nabi Muhammad SAW memperintahkan kepada Zaid bin Tsabit, seorang Sahabat Nabi dan penghimpun Al Quran, untuk belajar bahasa Ibrani dan bahasa Suryani yang digunakan orang-orang Yahudi.
Kekuatan daya ingat Zaid bin Tsabit telah membuatnya diangkat penulis wahyu dan surat-surat Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya, dan menjadikannya tokoh yang terkemuka di antara para sahabat lainnya. Diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit bahwa:
Rasulullah SAW berkata kepadanya "Aku berkirim surat kepada orang, dan aku khawatir, mereka akan menambah atau mengurangi surat-suratku itu, maka pelajarilah bahasa Suryani", kemudian aku mempelajarinya selama 17 hari, dan bahasa Ibrani selama 15 hari.
Penulis pun teringat ceramah mendiang Prof Dr Mohammed Arkoun di Jakarta. Guru Besar di Universitas Sorbonne, Prancis, itu menyatakan, Islam akan meraih kejayaannya jika umat Islam membuka diri terhadap pluralisme pemikiran, seperti pada masa awal Islam hingga abad pertengahan. Pluralisme bisa dicapai bila pemahaman agama dilandasi paham kemanusiaan, sehingga umat Islam bisa bergaul dengan siapa pun.
"Kolonialisme secara fisik memang telah berakhir. Namun, paling tidak, pemikiran kita masih terjajah, tidak ikut modern yang ditandai oleh kebebasan berpikir. Ini yang harus dilepaskan oleh umat Islam," kata Prof Arkoun dalam seminar "Konsep Islam dan Modern tentang Pemerintahan dan Demokrasi" di Jakarta 10 April 2000.
Dalam ceramahnya itu, Arkoun juga menekankan pentingnya pendidikan yang didasarkan pada humanisme. Dalam kaitan itu, di sekolah-sekolah menengah perlu diajarkan multibahasa asing, sejarah ,dan antropologi, serta perbandingan sejarah dan antropologi agama-agama. "Marilah kita terbuka pada semua kebudayaan dan terbuka pada semua pemikiran," kata Prof Arkoun pula.
Penting pemelajaran bahasa-bahasa asing alias bahasa di luar masyarakat kita memang amat penting.
Manfaatnya tentu tidak sekedar untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih besar, tetapi juga memahami kebudayaan kelompok lain untuk menghindari konflik.
Konflik-konflik dan bahkan perang yang dipicu oleh masalah kebahasaan banyak dicatat oleh para ahli, antara lain perang saudara di Srilanka antara kelompok Sinhala dan Tamil. Konflik yang telah menewaskan lebih dari 100.000 orang itu memang tampak sudah berakhir setelah banyak pemimpin utama Tamil telah tewas. Tetapi secara budaya belum.
Perselisihan perdagangan antarnegara, seperti Amerika Serikat dan Jepang juga disebabkan oleh ketidakpahaman bahasa dan budaya. Sekarang, AS dan Jepang memang memiliki hubungan politik, ekonomi dan militer yang baik. AS memandang Jepang sebagai salah satu partner terdekat. Jepang merupakan salah satu negara pro Amerika paling erat, dengan 85% rakyat Jepang memandang AS secara positif dan 87% rakyat AS memandang Jepang secara positif pada 2011. Tapi pada tahun 2014 angka itu turun dengan rakyat Jepang yang memandang positif AS hanya 66%. Sedang 81% rakyat AS tetap positif memandang Jepang pada 2013. (Wikipedia).
Perselisihan antarbangsa seperti AS dan Jepang bisa dipahami antara lain lewat buku karya Prof Haru Yamada, Different Games, Different Rules: Why Americans and Japanese Misunderstand Each Other (Oxford University Press, 1997).
Pengajar Universitas Westminter, Inggris, itu mengemukakan, bahwa meskipun hubungan politik dan ekonomi antara AS dan Jepang disebut erat, namun kedua negara itu sebenarnya masih jauh dari saling mengerti satu sama lain. Banyak alasannya mengapa hal itu terjadi. Ia menjelaskan, organisasi sosial membentuk cara kita berbicara. Karena budaya Amerika dan Jepang menghargai bentuk-bentuk hubungan sosial yang berbeda, mereka pun memainkan permainan bahasa dengan seperangkat aturan yang berbeda pula. Di Amerika misalnya, fabel Aesop tentang belalang dan sejumlah semut berakhir dengan semut-semut itu mengejek dan menyalahkan belalang tolol dan malas itu.
Namun di Jepang, akhir ceritanya berbeda: semut-semut itu mengundang sang belalang untuk makan bersama di musim dingin saat itu, karena mereka menghargai bagaimana nyanyian belalang itu menghibur mereka saat bekerja keras di musim panas. Dalam perbedaan antara akhir dua cerita itu, Yamada berpendapat adanya pelajaran penting: Orang-orang Amerika, karena sejarah politiknya yang unik, menghargai independensi dan individualitas. Sedang orang-orang Jepang menghargai saling ketergantungan dan keterkaitan satu sama lain.
Kedua bahasa itu dirancang untuk menunjukkan dan memperkuat nilai-nilai ini sehingga kata-kata, frasa-frasa dan kalimat-kalimat di satu bahasa dapat memiliki konotasi-konotasi yang sangat berbeda dengan bahasa lainnya. Ini membuka potensi salah pengertian. Dicontohkan pula bagaimana di Jepang sikap diam itu dihargai dan ucapan yang tersendat-sendat dinilai lebih jujur dan thoughtful dibanding ucapan yang lancar, sementara di Amerika orang menyukai pembicaraan yang langsung dan lancar.
Seberapa banyak kita perlu belajar bahasa asing? Tentu saja terserah masing-masing individu. Bagi mereka yang punya hobi belajar bahasa asing dan sangat berbakat, mungkin bisa seperti Ziad Fazah (64), the greatest living polyglot yang kini tinggal di Brasil. Dia menguasai 57 bahasa. Kardinal Mezoffanti (1774-1849) lancar 34 bahasa, Harold William (1876-1928) menguasai 58 bahasa, dan Drs RMP Sosrokartono (1877-1952), kakak kandung RA Kartini, fasih 24 bahasa. Sosrokartono yang belajar bahasa di Universitas Leiden ini pernah menjadi wartawan perang New York Herald Tribune selama Perang Dunia I di Eropa dan menjadi Kepala Penerjemah Liga Bangsa-Bangsa (Volkenbond).
Banyak bapak bangsa ini, seperti Soekarno, Agus Salim, dan Hatta, menguasai sejumlah bahasa. Atau banyak juga dari generasi sekarang, masih muda-muda, juga fasih beberapa bahasa asing.
Tapi mungkin tidak perlulah memaksa diri. Kalau seseorang siap mempelajari satu atau dua bahasa asing, plus berusaha memahami bahasa-bahasa daerah di sekitar kita, sungguh upaya yang patut diapresiasi. Konflik-konflik berbau SARA seperti yang terjadi antara orang-orang suku Dayak dan Madura di Kalimantan pada tahun 2000-an yang lalu semestinya juga dapat dihindari bila kedua kelompok itu saling menghargai, antara lain lewat pemahaman bahasa dan budaya. Warga Madura setidaknya mengerti dan memahami sedikit bahasa Dayak, begitu pula sebaliknya.
Anak-anak muda yang dibesarkan dengan bahasa-bahasa dan budaya di luar kelompoknya kiranya akan tumbuh sebagai orang-orang yang cenderung humanis dan pluralis. Mereka pun akan sangat memahami bahwa dalam galaksi bahasa, setiap suara seseorang adalah bintang. In a galaxi of languages, every person’s voice is a star. Atau seperti kutipan kata-kata Sosrokartono di atas, belajar bahasa berarti belajar bangsa. Artinya pula, belajar mengasah perasaan dan hati. Belajar mengasah rasa kemanusiaan. (*)

Djoko Pitono, veteran jurnalis dan ediror buku.