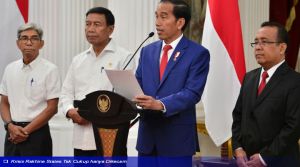COWASJP.COM – JAKARTA, 13 MEI 1998. Itulah tanggal terjadinya sebuah tragedy berdarah. Saat meletusnya “puncak bisul” massa yang sudah muak dengan pemerintahan Orde Baru (Orba) Soeharto.
Pagi itu, matahari bersinar terang. Udara pagi juga terasa nyaman. Tapi dalam tempo singkat, ibukota negara itu terbakar. Tidak hanya terbakar secara fisik, tapi juga terbakar emosi massa. Pasalnya, mereka baru saja mendengar isyu tertembaknya sejumlah mahasiswa demonstran.
Sekitar pukul 10.00 WIB pagi, massa mulai mengamuk. Sejumlah titik api bermunculan di seantero kota. Supermarket-supermarket besar dan pertokoan di berbagai wilayah dilalap api. Api yang tidak hanya membakar swalayan-swalayan mewah itu secara fisik, tapi juga tubuh manusia-manusia tak berdosa. Para karyawan toko-toko swalayan yang terperangkap di dalam kobaran api. Bahkan juga sebagian perusuh yang berniat menjarah. Ratusan nyawa – itu pun yang sempat terhitung beberapa waktu kemudian – melayang sia-sia.
Dalam tempo singkat pula, massa sudah memenuhi sisi-sisi jalan. Bis-bis umum, taxi, angkot, bahkan juga mobil-mobil pribadi yang lewat, disetop. Dibalikkan beramai-ramai. Lalu dibakar. Satuan-satuan polisi menghilang. Sebagian, di antara mereka yang masih berada di tengah massa, dikeroyok. Dipukuli, ditendang, dihajar massa perusuh sampai babak belur. Polisi-polisi malang itu berusaha menyelamatkan diri. Sebagian sambil copot seragam. Tidak mengerti mengapa mereka jadi sasaran amuk massa yang menggila.
Sampai larut malam, amuk massa dan aksi penjarahan tidak berhenti. Sebagian penduduk tercekam ketakutan. Jalanan kota, yang biasanya selalu dipadati kendaraan, jadi lengang. Lampu-lampu penerang jalan ditumbangkan. Tiang-tiangnya bergeletakan di tengah jalan. Kendaraan umum tak satu pun lagi yang berani lewat. Karenanya para buruh dan karyawan yang hendak pulang terpaksa jalan kaki berpuluh kilometer ke rumah masing-masing.
Bahkan dua hari kemudian, huru-hara belum juga berhenti. Tak hanya Jakarta, amuk massa ternyata juga melanda beberapa kota di Indonesia. Tim Adhoc Penyelidikan bentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berkenaan Kerusuhan Mei 1998 mencatat, kerusakan dan kematian mewarnai prahara.
Seperti disebut dalam dokumen tim Adhoc penyelidik tadi, setidaknya 13 kota dilanda prahara. Kota-kota itu meliputi Jakarta Raya – di dalamnya termasuk sebagian Tangerang dan Depok – lalu Solo, Klaten, Boyolali, Medan, Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Palembang, Surabaya, Lampung, Padang, dan Bandung. Yang paling penting untuk diingat, masing-masing kota punya cerita sendiri-sendiri, dengan korban manusia dan harta benda yang tidak sedikit.
Satu minggu kemudian, tepatnya 21 Mei 1998, kekuasaan Orde Baru Soeharto yang sudah bercokol 32 tahun pun tumbang. Sungguh tak terbayangkan sebelumnya bahwa tragedi itu akan terjadi. Pagi hari 21 Mei 1998, dengan suara bergetar, orang kuat Orde Baru itu menyatakan pengunduran dirinya sebagai presiden.
Terlalu banyak orang yang terpaksa harus meratap karena kehilangan anak dan sanak saudara dalam tragedi berdarah itu. Sebagian dari mereka bahkan sampai hari ini meratapi nasib anak-anak gadis mereka yang direnggut kehormatannya oleh orang-orang jahat. Orang-orang jahat yang bahkan lebih jahat dari pada hewan dan binatang melata sekalipun.
*
BILA DISIMPULKAN, sejatinya seluruh anak bangsa ini meratap mengenang kejadian seperti itu. Tapi bila kita telusuri lebih jauh perjalanan sejarah kita, anak bangsa yang terkenal santun dan pemaaf ini sebenarnya bisa juga lebih buas dari pada binatang buas. Kejadian-kejadian memilukan terus saja terulang dan terulang. Semua itu membuktikan, kita tidak pernah belajar dari sejarah. Terutama sejarah kita yang kelam.
Ketika republik ini belum berumur setahun jagung – tepatnya 18 September 1948 – kita disibukkan oleh pemberontakan yang lebih dikenal dengan Peristiwa Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan partai-partai kiri lainnya yang tergabung dalam organisasi bernama "Front Demokrasi Rakyat" (FDR).
 ILUSTRASI: Lubagn Buaya, Foto: istimewa
ILUSTRASI: Lubagn Buaya, Foto: istimewa
Kita tahu, kaum pemberontak PKI berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yaitu: Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Meskipun kita tahu, tapi kita tahunya sudah terlambat. Pemberontakan sudah terjadi. Korban berjatuhan dari pihak-pihak yang tidak berdosa, terutama dari kalangan kiyai dan ulama. Mereka diculik, lalu dibantai.
Ketika aksi mereka berhasil ditumpas, giliran rakyat yang marah membantai mereka. Dalam aksi balas dendam itu, mayat-mayat mereka kemudian dilemparkan ke Kali Madiun. Karenanya air kali yang sebelumnya bening dalam waktu singkat berubah warna jadi warna darah.
Pada peristiwa yang lain. Tepatnya 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Husein mendeklarasikan apa yang dikenal dengan sebutan “Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia” (PRRI). Pada awalnya ini merupakan gerakan penentangan terhadap pemerintah pusat oleh daerah-daerah. Sebagian sejarawan menganggap hal itu dipicu oleh ketidakpuasan daerah terhadap masalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Pemerintah pusat menyatakan gerakan ini sebagai pemberontakan. Pemberontakan yang ternyata pada 17 Februari 1958, atau dua hari kemudian, didukung oleh gerakan serupa di Sulawesi. Gerakan ini lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Perjuangan Rakyat Semesta” (Permesta). Proklamasi di Sulawesi dipelopori oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual, yang waktu itu merupakan Panglima Wirabhuana.
Karenanya kedua gerakan ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan PRRI/PERMESTA.
Persoalannya, benarkah itu terjadi hanya karena penentangan daerah terhadap pemerintahan pusat disebabkan masalah otonomi daerah, khususnya perimbangan keuangan daerah dan pusat? Menurut beberapa tokoh yang terlibat langsung dalam peristiwa itu, penyebab utama timbulnya penentangan itu adalah karena mereka tidak lagi percaya kepada Presiden Soekarno. Karena Soekarno begitu dekat atau bahkan bisa dikatakan sudah dikendalikan oleh Partai Komuni Indonesia (PKI).
Sebagian dari mereka yang terlibat PRRI – seperti Syafruddin Prawiranegara dan Natsir – mengaku sebelumnya sama sekali tidak tahu rencana pendeklarasian gerakan itu. Tapi mereka terjebak dalam pertentangan pusat dan daerah itu dan tidak bisa lagi menghindar ketika Letkol Ahmad Hussein mendeklarasikan gerakan, sementara mereka pas berada di daerah itu. Menurut mereka, gerakan itu sejatinya merupakan gerakan koreksi terhadap pemerintah pusat.
Untuk menumpas gerakan itu, pemerintah Indonesia melakukan Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Itulah aksi penumpasan pemberontak terbesar dalam sejarah militer Indonesia, sehingga menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit.
Pada 30 September 1965, peristiwa paling memilukan justru terjadi lagi. PKI yang sudah merasa di atas angin melakukan pemberontakan kembali. Para pimpinan militer kita diculik dan dibantai. Mayat mereka dilemparkan begitu saja ke dalam sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Yang patut dicatat, kita selalu lupa. Kita selalu lupa punya musuh dalam selimut. Yang tega menohok kawan seiring. Yang suka menggunting dalam lipatan. Kita bangga sebagai bangsa yang santun dan pemaaf. Tapi kita selalu lupa betapa banyak darah dan airmata anak bangsa yang terbuang sia-sia.
Sekarang, 19 tahun sudah kita melewati suasana aksi reformasi yang menggelora. Kita begitu bangga dengan demokrasi kita. Kita begitu bangga dengan kebebasan pers kita, kebebasan berserikat kita, kebebasan berbicara kita dan bahkan kebebasan dalam banyak hal. Padahal kita tidak sadar sepenuhnya bahwa kebebasan yang kita peroleh masih semu alias palsu. Kita selalu lupa siapa sejatinya musuh utama dan bersama kita. Kita selalu lupa karena melupakan sejarah kita.
Jangan sampai terulang kembali darah dan airmata anak bangsa ini tumpah sia-sia. Hanya karena kita “Makhluq Pelupa Sejarah”! (*)